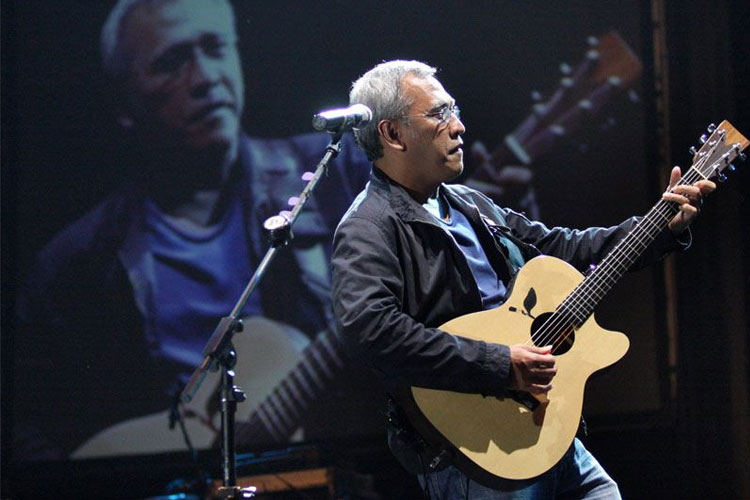TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Agustus 2025 menjadi titik tolak salah satu sejarah besar di Indonesia. Sejarah dimana amarah rakyat sudah tidak dapat dibendung lagi. Agustus tidak lagi hanya dirayakan untuk menyambut kemerdekaan simbolis, namun kemerdekaan yang sudah terengut dari para oknum pejabat dan parlementernya.
Demo demi demo bermunculan rentang akhir Agustus sampai 1 September lalu. Kejadian dan tragedi mulai bermunculan, dari penjarahan rumah pejabat, perusakan fasilitas umum, sampai penyerangan kampus dan meninggalnya beberapa pejuang demokrasi dari banyak lini, mahasiswa dan pengemudi transportasi online.
Tragedi-tragedi yang muncul ditengah aksi-aksi protes ini menambah luapan amarah masyarakat dan menggoyah fokus tujuan utama dari protes yang sesungguhnya.
Media arus utama dan media massa tampak menyiarkan aksi-aksi protes yang terjadi di banyak wilayah. Menariknya, yang disorot bukanlah pesan utama dari protes itu atau para demonstran. Seperti lagu lama, penjarahan dan aksi-aksi negatif lainnya yang menjadi bahasannya.
Lebih menarik lagi, di setiap kesempatan aksi agaknya media menyoroti peran pejabat atau kepala daerah yang turun menemui massa. Seakan menebar pesan baik-baik saja dari aksi-aksi massa yang terjadi.
Memang tidak dapat dipungkiri aksi protes masyarakat lebih damai jika dibandingkan demo besar yang terjadi tahun 1998. Namun, yang perlu digaris bawahi tokoh utama dari aksi protes adalah protester (demonstran) beserta spanduk-spanduknya, bukan kepala daerah, pejabat bahkan ulamanya.
Fenomena ini seakan menggiring opini aksi protes berlangsung baik-baik saja. Padahal esensi dari aksi protes adalah didengarkannya tuntuan rakyat, diserap aspirasinya dan dieksekusi.
Esensi aksi protes bukan doa bersama, esensi aksi protes bukan juga bagaimana pejabat daerah menemui massa. Meski dampak hadirnya kepala daerah di tengah aksi cukup dapat menekan kekerasan-kekerasan yang mungkin terjadi.
Namun, esensi dari protes itu sendiri akhirnya redup dibalik kata damai yang memang diharapkan. Mengingat esensi inti dari aksi protes yang berlangsung saat ini yaitu 17+8 tuntutan rakyat (transparansi, reformasi, empati).
Dari gambaran aksi protes yang ditampilkan media ada upaya menggoyah fokus utama rakyat. Jika melalui provokator sudah tidak mempan menggoyah fokus rakyat atas tuntuannya, yang terjadi di media hari ini seperti mengalihkan fokus utama yang selama ini menjadi keresahan. Keresahan akan pajak yang semakin bertambah, pejabat yang semakin tinggi tunjangannya, dan kesenjangan antara rakyat dan wakilnya yang semakin tinggi.
Semua terkaburkan dengan fokus sorotan hadirnya pejabat atau kepala daerah di tengah aksi. Disinilah literasi politik di masyarakat sangatlah perlu, masyarakat harus selalu merasa resah dengan segala yang terjadi dalam pemerintahan.
Melihat bagaimana para kepala daerah hadir di tengah-tengah aksi massa merepresentasikan bagaimana mereka mengamankan nama mereka untuk pemilu selanjutnya, bahasa ekstrimnya kampanye. Bak gayung bersambut, momentum ini menjadi makanan lezat media dan buzzer untuk membantu mengamankan posisi para pejabat.
Tampilan yang indah untuk dipertontonkan ditambah kehadiran ulama dan acara aksi berubah menjadi doa bersama. Maka, bagaimana aksi protes yang terjadi di bundaran UGM Jogja dan beberapa tempat lain di Jogja dijaga sedemikian rupa agar pesan dapat terbaca dan tersampaikan dengan baik, bukan kerusakan atau kerusuhan.
Tetapi dapat kita soroti bersama, seberapa banyak media menyoroti pesan aksi massa baik itu dalam bentuk orasi dan spanduknya? Tidak sebanyak bagaimana media dan konten media sosial yang hanya memberitakan menampilkan kondisi damainya saja.
Dari sinilah pemahaman dan literasi politik agaknya perlu ditanamkan lagi. Mungkin representasi aksi protes selama ini cenderung negatif, karena memang seperti itulah bagaimana yang ditampilkan di media selama ini.
Framming bahwasanya aksi protes merupakan kegiatan negatif dengan terus menyorot kekerasan-kekerasan yang terjadi. Namun, saat semua kekerasan-kekerasan itu sulit ditemukan pada aksi protes maka yang dilakukan adalah menghilangkan fokus akan tuntutan dari aksi protes itu sendiri.
Maka dapat kita lihat bagaimana pemberitaan yang beredar, bukan 17+8 tuntutan rakyat (transparansi, reformasi, empati), melainkan kebaikan-kebaikan pemimpin dan pejabat yang menghadiri aksi. Lagi-lagi bukan ”jangan terprovokasi”, tapi ”jangan terdistraksi” dengan fokus lain.
***
*) Oleh : Fuandani Istiati, Dosen Ilmu Komunikasi UAD.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |