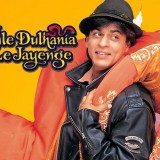TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Setiap tahun, menjelang Hari Pahlawan 10 Nopember, bangsa ini kembali diingatkan akan wajah lamanya dalam cermin sejarah. Wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional selalu memecah ruang publik.
Sebagian menilai ia penyelamat yang membawa stabilitas dan pembangunan, sebagian lagi menolak keras, mengingat pelanggaran HAM, represi politik, dan warisan otoritarianisme yang membekas hingga kini.
Padahal ada persoalan mendasar dan lebih sunstansial yang justru luput dan tidak menjadi perhatian kita, bangsa ini belum pernah benar-benar berdamai dengan dirinya sendiri.
Seharusnya perdebatan bukan sekadar soal siapa yang layak disebut pahlawan, tapi tentang bagaimana bangsa ini memahami masa lalu, mengakui luka sejarah, menghukum yang salah dan saling memaafkan untuk membangun masa depan yang bermartabat.
Sejak awal kemerdekaan, sejarah ditulis oleh tangan penguasa. Yang kalah dilupakan, yang berkuasa dimuliakan, yang berbeda dibungkam. Yang menang dan berkuasa di agung-agungkan dan ketika lengser dihina dinakan, mau sampai kapan?
Kita membangun monumen untuk kemenangan, tapi jarang menundukkan kepala untuk mengenang luka. Sejarah pun menjadi panggung eksistensi, bukan cermin mawasdiri.
Di masa Orde Baru, pengendalian memori dan nalar publik menjadi bagian dari kekuasaan. Buku sejarah disusun untuk membentuk persepsi tunggal, film dan media dijadikan alat penegasan, dan narasi “stabilitas nasional” menggantikan kebenaran getir yang dialami rakyat.
Kekuasaan menciptakan ingatan yang patuh, di mana penderitaan dibungkam dan rasa bersalah disamarkan atas nama pembangunan. Akibatnya, bangsa ini tumbuh dengan trauma yang diwariskan. Kita dipaksa belajar melupakan lebih cepat daripada memahami.
Kini, ketika wacana kepahlawanan Soeharto muncu kembali, kita seperti dipaksa menatap cermin itu lagi, tetapi tetap dengan cara yang salah, penuh kepalsuan, tanpa keberanian moral. Seperti dikatakan Virdika Rizky Utama (NU Online, 2025), penilaian atas kepahlawanan seharusnya didasarkan pada keberanian etis, bukan pada keberhasilan administratif.
Pahlawan atau Penguasa?
Pahlawan sejati bukanlah mereka yang paling lama berkuasa, tetapi yang paling berani mempertaruhkan diri demi kemanusiaan dan keadilan. Keberhasilan membangun jalan, bendungan, atau stabilitas ekonomi tidak dapat menghapus darah dan air mata rakyat yang dikorbankan. Bangsa yang nalarnya masih nalar mediatik mudah kehilangan kompas moral dan malah menjadikan pelaku kekerasan sebagai simbol kebesaran.
Kini kepahlawanan dibirokratisasi, cukup berkas administratif, tanda tangan politik, dan sebuah rapat tim seleksi yang ditunggangi, seorang tokoh bisa diabadikan. Padahal gelar pahlawan nasional seharusnya lahir dari kesaksian nurani, bukan dari mekanisme politik dan kekuasaan. Di sinilah yang sakit, bukan hanya sejarah bangsa, tetapi juga cara bangsa ini mengenang masa lalunya.
Bangsa ini bukan kekurangan pahlawan, tetapi keberanian untuk jujur. Ibarat tubuh yang sakit parah, bangsa ini menutupi gejala dengan kosmetik retorika.
Kita bicara tentang pembangunan, visi 2045, dan transformasi digital, tapi tidak pernah mau menyentuh trauma 1965, pelanggaran HAM, atau korupsi sistemik yang diwariskan.
Jika penyakit kronis bangsa tidak didiagnosis dengan jujur, ia tidak akan pernah sembuh, ia hanya berpindah bentuk, bahkan dipupuk untuk dijadikan komoditas politik. Dan semasih sakit "jiwa dan kesadaran bangsa" ini jangan pernah berharap kita akan menjadi bangsa yang besar.
Rekonsiliasi sejati membutuhkan pengakuan, bahwa kekerasan, ketidakadilan, dan kebohongan adalah bagian dari sistem yang akut selama ini, bukan sekadar kesalahan individu. Tanpa kesadaran dan keberanian moral, negara tidak akan bisa memimpin proses penyembuhan "penyakit laten sejarah" bangsa ini.
Seperti diingatkan oleh Gus Dur, bangsa ini penakut. Takut pada kebenaran, takut pada refleksi, takut kehilangan legitimasi, takut untuk jujur dan menindak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Padahal bangsa yang besar bukanlah yang tak memiliki luka, melainkan yang berani menghadapinya dengan kepala tegak.
Afrika Selatan telah membuktikan hal itu melalui Truth and Reconciliation Commission , sementara Indonesia masih memilih stabilitas semu di atas luka yang belum sembuh dan terus dipelihara oleh kepentingan tertentu.
Gus Dur, Mas Imam Aziz, dan Jalan yang Pernah Dibuka
Bangsa ini sesungguhnya pernah memiliki arah penyembuhan dan pertobatan nasional, ketika Gus Dur, sebagai tokoh NU dan Presiden, berencana mengambil langkah moral monumental dengan mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang komunisme dan menyampaikan permintaan maaf terbuka atas nama negara atas korban-korban kejadian saat itu.
Langkah itu bukan untuk membela ideologi tertentu, tetapi mengembalikan martabat kemanusiaan yang diinjak sejarah karena hakikatnya semua pihak merupakan korban konspirasi jahat.
Mas Imam Aziz menterjemahkan gagasan Gus Dur kedalam Syarikat (Masyarakat Santri Peduli Advokasi Rakyat) sebuah gerakan masyarakat sipil, melalui penelitian, advokasi, menelusuri kebenaran sejarah dan menulisnya menjadi buku serta yang paling radikal mempertemukan para korban dan pelaku dari berbagai latar belakang, eks tapol, keluarga korban, dan masyarakat pesantren. Di ruang-ruang kecil itu, dialog dilakukan tanpa dendam, rekonsiliasi lahir dari hati, bukan seremoni politik.
Namun langkah moral ini terhenti, tidak mendapat dukungan apalagi apresiasi. Negara yang seharusnya memimpin proses penyembuhan dan rekonsiliasi justru diam, atau bahkan menertawakan mereka yang mencoba mengingat untuk saling memaafkan.
Diam dan pembiaran yang terus menerus membuat luka jiwa bangsa ini menjadi semakin kronis kompleks. Kita hidup dalam paradoks dan kemunafikan kolektif, sebagai bangsa religius yang takut mengakui dosa historisnya sendiri.
Di tengah kebuntuan negara, pesantren memiliki potensi besar menjadi jantung penyembuhan bangsa. Pesantren menyimpan tradisi islah, saling memaafkan, memperbaiki dan mendamaikan. Ia tidak hanya mendidik akal, tetapi juga mengasah hati nurani.
Sayangnya, kesadaran ini masih bersifat personal, muncul dalam inisiatif individu seperti Gus Dur, Mas Imam Aziz, atau beberapa kiai desa yang membuka ruang dialog diantara sesama korban disekitar mereka. Bayangkan jika ini menjadi kesadaran kolektif bangsa ini.
Agar efektif, pesantren harus meneruskan apa yang telah dilakukan Gus Dur dan Mas imam, menggeser gerakan ini dari ruang ibadah menjadi ruang rekonsiliasi sosial. Santri perlu dididik membaca luka bangsa, bukan sekadar kitab. Karena pada akhirnya, rekonsiliasi adalah bagian dari jihad kemanusiaan, menegakkan kebenaran tanpa menebar dendam.
Pertama, Melakukan pertaubatan nasional melalui rekonsiliasi yang Jujur dan berkelanjutan. Negara harus memimpin pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemulihan martabat korban, dan penulisan ulang sejarah dengan jujur. Proses ini tidak bisa berhenti pada seremoni politik tahunan. Langkah ini bisa dilakukan dengan membentuk tim rekonsiliasi sebagaimana di Afrika.
Kedua, Memperkuat peran pesantren dan masyarakat sipil, gerakan seperti Syarikat perlu diperluas menjadi gerakan sosial-keagamaan yang berkelanjutan dan lintas generasi, tidak bergantung pada momen politik.
Ketiga, Redefinisi makna kepahlawanan dan melakukan moratorium pemberian gelar pahlawan sampai "luka laten sejarah" jiwa bangsa ini disembuhkan secara total dengan rekonsiliasi nasional.
Keempat, Merubah kurikukum pendidikan moral sejarah anak bangsa yang jujur dan secara etis, bukan politis dan ideologis semata, karena mengakui kesalahan bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral yang membebaskan.
Rekonsiliasi nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, syarat mutlak agar bangsa ini dapat berdiri tegak sebagai masyarakat beradab. Dan rekonsiliasi hanya mungkin jika negara, masyarakat sipil, dan pesantren berjalan bersama, membuka ingatan, menata hati, dan membangun masa depan tanpa dendam.
Bangsa ini mungkin tidak akan kekurangan atau kehilangan pahlawan, tetapi kehilangan keberanian untuk mengingat dengan jujur. Kita sibuk menentukan siapa yang dipuja, siapa yang disalahkan, padahal keduanya hanyalah cermin dari wajah kita sendiri.
Ada luka yang diwariskan tanpa pengakuan, di mata ibu kamisan yang kehilangan anaknya, di hati petani yang kehilangan tanahnya, di dada para korban eks tapol yang dirampas hak-haknya, luka itu menurun seperti doa yang tak kunjung sampai.
Di tengah kebisuan itu, pesantren menyalakan lentera kecil, lentera yang tak menyalahkan, tapi menyembuhkan, yang tidak mengutuk masa lalu, tapi menatapnya dengan belas kasih.
Karena sejatinya, kemaafan tanpa kebenaran hanyalah penyangkalan, dan kebenaran tanpa kasih sayang hanyalah kekerasan dalam bentuk lain.
Tugas kita hari ini bukan menambah daftar nama di dinding kepahlawanan, melainkan menulis bab baru kesadaran bangsa, keberanian terbesar bukan menggulingkan penguasa atau mengutuk para pelaku kejahatan, tetapi mengalahkan diri sendiri yang takut pada kebenaran sejarah masa lalu.
Seperti Mandela menyalakan cahaya dari penjara, atau Gus Dur memilih jalan maaf di tengah kebencian, kita pun harus berani percaya bahwa bangsa ini bisa disembuhkan, asal berani mengingat, mengaku, dan mencintai sesama bangsanya untuk saling memaafkan.
Bangsa yang berani menatap masa lalunya dengan jujur itulah bangsa yang layak berjalan menuju masa depan dengan kepala tegak. Itulah makna sejati kepahlawanan, bukan nama yang diukir di batu nisan dan kertas penghargaan, apalagi dengan rekayasa dan dipaksakan. Pahlawan sejati akan terukir dan terus hidup dalam nurani bangsa ini dan setiap orang yang memilih jalan kebenaran.
Saat ini “Tidak penting lagi siapa yang akan disebut dan dapat gelar pahlawan, yang lebih penting bagi bangsa ini adalah bagaimana berani jujur pada nuraninya, untuk membongkar dan mengakui setiap kesalahan dan kejahatan masa lalu untuk saling memaafkan” begitu kira-kira jawaban, kalau Gus Dur dan Mas Imam Azis ditanya.
***
*) Oleh : Mohammad Alfuniam, Direktur Pusat Studi Pesantren Masa Depan UNU Yogyakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |