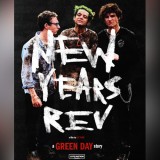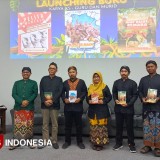TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Di era ketika setiap klik, transaksi, hingga obrolan virtual harus berlangsung dalam sepersekian detik, kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya: apa yang menopang semua itu? Jawabannya sederhana sekaligus mengejutkan, yaitu; waktu.
Bukan hanya jam di tangan atau kalender di dinding, melainkan waktu universal yang menjadi denyut nadi jaringan digital global. Dari server Google, sistem GPS, hingga transaksi keuangan internasional, semuanya bergantung pada ketepatan waktu. Namun, ada fakta rapuh yang sering terlupakan: waktu digital ternyata bersandar pada rotasi Bumi, sesuatu yang tidak sepenuhnya stabil.
Bumi tidak berputar dengan kecepatan konstan. Panjang satu hari (yang kita anggap selalu 24 jam) sesungguhnya bisa lebih pendek atau lebih panjang dalam hitungan milidetik. Gempa besar, pencairan es kutub, hingga perubahan di inti Bumi bisa menggeser ritme ini.
NASA mencatat, pada 19 Juli 2020, Bumi berputar lebih cepat 1,4602 milidetik dibanding hari normal. Bagi kehidupan sehari-hari, deviasi itu tak terasa. Tetapi bagi server global yang harus sinkron sempurna, selisih sekecil itu bisa berarti kekacauan.
Untuk mengimbangi fluktuasi tersebut, sejak 1970-an para ilmuwan menambahkan “leap second” (satu detik ekstra) pada waktu universal terkoordinasi (UTC). Namun tambahan sederhana ini bisa mengguncang dunia digital.
Ketika leap second disisipkan pada 2015, beberapa layanan besar seperti Reddit dan LinkedIn sempat tumbang. Sistem komputer yang dibangun dengan asumsi hari selalu sama panjangnya tak siap menghadapi tambahan sekecil itu.
Google lalu mengembangkan trik bernama leap smear: alih-alih menambahkan satu detik sekaligus, mereka menyebarkannya perlahan selama 20 jam. Solusi itu memang efektif, tetapi sekaligus mengungkap bahwa waktu bukanlah entitas netral. Ia bisa direkayasa sesuai kepentingan perusahaan teknologi.
Pertanyaan pun muncul: siapa sebenarnya yang berhak menentukan waktu? Apakah ilmuwan yang memantau rotasi Bumi, atau perusahaan teknologi yang menjalankan mesin digital kita?
Inilah titik di mana waktu berubah dari sekadar instrumen teknis menjadi arena politik dan ekonomi. Badan internasional IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) berencana menghapus leap second mulai 2035 demi stabilitas sistem digital.
Raksasa teknologi Amerika mendukung penuh, sebab bagi mereka tambahan satu detik sama dengan potensi kerugian miliaran dolar akibat server kacau.
Sebaliknya, Rusia dan China menolak. Bagi kedua negara ini, waktu adalah bagian dari kedaulatan. Sistem navigasi satelit seperti BeiDou dan GLONASS bergantung pada presisi waktu, dan menyerah pada standar baru berarti membuka ruang dominasi geopolitik.
Paradoks pun terbuka lebar. Di satu sisi, komunikasi global menuntut sinkronisasi tanpa cela. Di sisi lain, fondasi geofisika Bumi terus berubah, menolak untuk tunduk pada logika akselerasi digital. Ketika dua dunia ini bertabrakan, lahirlah krisis yang tak hanya teknis, melainkan epistemik; krisis pengetahuan tentang apa itu waktu.
Filsuf Paul Virilio pernah mengatakan, kekuasaan modern bertumpu pada kecepatan. Dalam komunikasi digital, kecepatan mustahil tanpa waktu yang stabil. Maka, siapa yang mengatur waktu, ia mengatur arus informasi.
Ketika Google menciptakan versi waktu mereka sendiri melalui leap smear, mereka sejatinya sedang merancang ulang ritme dunia. Hal serupa terjadi ketika negara menolak penghapusan leap second dengan alasan kedaulatan.
Waktu, yang dulu dianggap netral, kini menjadi alat kontrol. Implikasi sosialnya pun luas. Ketergantungan mutlak pada waktu digital membuat batas antara ruang pribadi dan publik kian kabur. Setiap klik, percakapan, hingga lokasi terekam secara presisi, menciptakan peluang pengawasan yang nyaris total.
Secara interpersonal, ritme digital yang menuntut kecepatan tanpa jeda menggerus ruang hening dalam komunikasi manusiawi. Interaksi semakin dangkal, seolah kualitas bisa digantikan oleh kuantitas koneksi.
Di tingkat global, muncul kesenjangan baru: “kesenjangan waktu.” Negara dengan infrastruktur digital yang kuat mampu mengikuti sinkronisasi presisi, sementara negara berkembang akan semakin jauh tertinggal, bahkan dalam hal vital seperti sistem peringatan dini bencana. Waktu, yang semestinya universal, justru memperdalam jurang ketidaksetaraan.
Di sinilah esensi temuan kritis penelitian interdisipliner tentang waktu sebagai infrastruktur komunikasi: waktu tidak lagi bisa dipandang sebagai angka netral di layar.
Ia adalah produk sosial-teknologis, hasil tarik-menarik antara geofisika, algoritma, dan kepentingan politik. Setiap detik dalam komunikasi digital adalah hasil kompromi rumit, bukan kepastian absolut.
Apakah kita harus cemas? Tidak selalu. Kesadaran bahwa waktu rapuh justru bisa membuka ruang refleksi. Jika selama ini kita sibuk mengejar kecepatan, mungkin saatnya mengakui bahwa ritme hidup kita ditentukan oleh sesuatu yang lebih luas dari sekadar jam atom atau server Google; yakni planet tempat kita berpijak.
Menyadari bahwa komunikasi digital berakar pada rotasi Bumi yang tak stabil mengajarkan kerendahan hati: teknologi setinggi apa pun tetap tunduk pada alam.
Perebutan waktu adalah perebutan atas ritme hidup manusia. Apakah ritme itu akan ditentukan oleh alam, oleh negara, atau oleh perusahaan teknologi raksasa; itulah pertanyaan besar abad digital ini. Sebab siapa yang menguasai waktu, dialah yang menguasai komunikasi, dan pada akhirnya, menguasai dunia. (*)
***
*) Oleh : Dr. Fajar Dwi Putra, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |